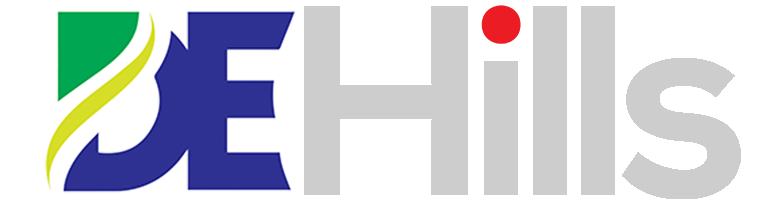Di atas langit ketujuh, Rasulullah ﷺ berdiri di hadapan Allah SWT, dalam sebuah pertemuan yang melampaui nalar manusia. Di Sidratul Muntaha, tempat yang tak terbayangkan oleh imajinasi, Nabi Muhammad ﷺ menerima perintah langsung dari Allah SWT: shalat lima puluh waktu dalam sehari. Namun, dalam perjalanan turun, sebagaimana sering diceritakan, beliau bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa, dengan segala keutamaan dan pengalamannya, menyarankan Rasulullah ﷺ untuk kembali kepada Allah dan meminta keringanan. “Umatmu tidak akan mampu,” katanya. Dialog ini, seperti yang kita dengar berulang kali, berlanjut hingga akhirnya jumlah shalat menjadi lima waktu sehari.
Kisah ini begitu populer, disampaikan oleh banyak penceramah dan termaktub dalam sejumlah literatur hadis. Namun, apakah kisah ini benar? Apakah masuk akal bahwa Nabi Muhammad ﷺ, pemimpin umat terakhir yang membawa syariat paling sempurna, membutuhkan nasihat dari Nabi Musa AS tentang bagaimana menyampaikan kewajiban shalat kepada umatnya? Ataukah kisah ini hanyalah riwayat yang tersusup dari tradisi lain, sebuah israiliyat yang akhirnya melahirkan cerita yang diterima tanpa kritik?
Logika di Balik Mukjizat
Isra Mi’raj adalah perjalanan agung yang menjadi salah satu bukti keistimewaan Nabi Muhammad ﷺ. Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Isra ayat 1:
> “Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
Perjalanan ini, baik Isra (dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa) maupun Mi’raj (naik ke langit hingga Sidratul Muntaha), adalah bukti hubungan langsung antara Allah SWT dan Rasulullah ﷺ. Perintah shalat diberikan tanpa perantara, sebuah tanda kedekatan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Lantas, bagaimana mungkin dalam peristiwa sebesar ini, Nabi Muhammad ﷺ seakan membutuhkan “bantuan” dari Nabi Musa AS?
Menggugat Narasi Dialog dengan Nabi Musa AS
Narasi yang populer ini memuat unsur yang menimbulkan pertanyaan mendasar. Misalnya, Allah SWT adalah Maha Mengetahui, yang telah menetapkan syariat dengan sempurna untuk umat manusia hingga akhir zaman. Jika perintah shalat ditetapkan sebanyak lima puluh waktu, bukankah itu sudah pasti sesuai dengan kemampuan manusia? Kisah ini seakan menggambarkan Allah “mengubah keputusan-Nya” setelah saran dari Nabi Musa AS, sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat Allah sebagai Zat yang Maha Bijaksana dan Maha Tahu.
Kisah ini juga menimbulkan pertanyaan tentang posisi Nabi Muhammad ﷺ. Beliau adalah Nabi terakhir yang membawa syariat yang sempurna, sebagaimana firman Allah SWT:
> “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridai Islam itu menjadi agamamu.” (QS. Al-Ma’idah: 3)
Apakah pantas jika seorang nabi yang menerima wahyu langsung dari Allah SWT membutuhkan saran dari nabi sebelumnya dalam hal syariat? Ini adalah narasi yang seolah-olah merendahkan keistimewaan Rasulullah ﷺ sebagai penutup para nabi.
Asal-Usul dan Pengaruh Israiliyat
Kisah ini memiliki banyak kemiripan dengan narasi-narasi dalam tradisi Yahudi, di mana Nabi Musa AS sering digambarkan sebagai figur utama dalam dialog dengan Tuhan. Tradisi ini, melalui literatur israiliyat, tampaknya memengaruhi beberapa riwayat yang masuk ke dalam tradisi Islam. Riwayat-riwayat israiliyat sering kali membawa cerita dramatis, yang menarik perhatian tetapi tidak memiliki dasar yang kokoh dalam Al-Qur’an atau hadis shahih.
Para ulama hadis, seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim, telah berusaha memilah mana hadis yang shahih dan mana yang tidak. Namun, dalam tradisi populer, kisah seperti ini sering kali disampaikan tanpa kritik, karena sifatnya yang menghibur dan mudah dicerna. Padahal, esensi Isra Mi’raj adalah hubungan langsung antara Allah SWT dan Rasulullah ﷺ, bukan perantara atau nasihat dari nabi lain.
Analisis Ayat dan Logika Syariat
Dalam Surah An-Najm ayat 13-18, Allah SWT berfirman:
> “Dan sungguh, dia (Muhammad) telah melihatnya (Jibril) pada waktu yang lain, di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. (Muhammad melihat Jibril) ketika Sidratul Muntaha diliputi sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya (Muhammad) tidak menyimpang dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sungguh, dia telah melihat sebagian tanda-tanda (kebesaran) Tuhannya yang paling besar.”
Ayat ini menegaskan bahwa Rasulullah ﷺ menyaksikan langsung tanda-tanda kebesaran Allah di Sidratul Muntaha. Dialog yang terjadi adalah antara Allah SWT dan Nabi Muhammad ﷺ, tanpa campur tangan dari nabi-nabi lain. Fakta ini memperkuat pandangan bahwa kisah Nabi Musa AS menyarankan keringanan shalat mungkin tidak sesuai dengan esensi peristiwa Isra Mi’raj.
Mengembalikan Esensi Isra Mi’raj
Isra Mi’raj bukan sekadar perjalanan luar biasa, tetapi juga ujian keyakinan bagi umat Islam. Peristiwa ini mengajarkan bahwa mukjizat tidak harus selalu dipahami dengan logika manusia, tetapi melalui iman kepada wahyu Allah SWT. Kisah Nabi Musa AS dalam narasi Isra Mi’raj, jika diterima tanpa kritik, dapat mengaburkan pesan utama dari peristiwa ini: bahwa syariat Islam adalah kesempurnaan yang langsung dari Allah SWT kepada Rasulullah ﷺ.
Meneguhkan Keyakinan
Sebagai umat Islam, kita harus terus kritis terhadap narasi-narasi yang beredar di sekitar kita, termasuk yang populer dalam ceramah. Bukan untuk meragukan tradisi, tetapi untuk memastikan bahwa keyakinan kita didasarkan pada kebenaran yang kokoh. Isra Mi’raj adalah peristiwa yang menegaskan kedekatan Nabi Muhammad ﷺ dengan Allah SWT, bukan tentang nasihat dari nabi-nabi lain. Semoga kita termasuk golongan yang mampu menangkap esensi murni dari peristiwa ini dan menjadikannya pelajaran dalam memperkokoh iman dan keyakinan kita.