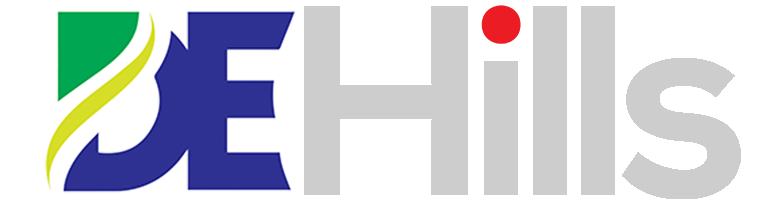Ketika fajar merekah di ufuk timur, sesungguhnya ia sedang menyapa seluruh manusia tanpa pernah bertanya tentang keyakinan apa yang kita peluk. Lembayung senja pun memeluk dunia dengan sikap yang sama—memberi cahaya pada siapa saja, tanpa membedakan suku, bangsa, atau agama. Di balik keindahan alam yang tidak pilih kasih ini, kita justru sering menyaksikan manusia terpecah karena perbedaan penafsiran dan label-label keagamaan. Padahal, apabila direnungkan lebih dalam, semua agama lahir dari satu sumber yang sama: Ketunggalan Ilahi.
Dalam narasi kuno, kita mengenal Dewa Brahma dalam Hindu, sebagian meyakini tersirat kisah Nabi Ibrahim. Dewi Saraswati yang penuh kebijaksanaan bergaung dalam kisah Siti Sarah. Para pemuka agama menegaskan bahwa Sang Buddha, Sidarta Gautama, mungkin berkelindan dengan cerita Nabi Zulkifli. Sementara Yesus Kristus yang membawa kabar keselamatan dalam tradisi Kristen, di kalangan Muslim dihormati sebagai Isa Al-Masih, putra Maryam. Demikianlah, rangkaian nama dan ragam penampilan ini justru menegaskan bahwa cinta kasih adalah bahasa yang mempersatukan kita, tanpa pernah absen di dalam setiap ajaran.
Akan tetapi, manusia dengan segala keindahannya juga menyimpan kepingan kerapuhan. Setiap hati membawa kemungkinan disusupi ego, amarah, serta kecenderungan menganggap diri paling benar. Iblis, yang sejak awal memandang manusia sebagai agen kehancuran, tak henti membisikkan rasa benci dan curiga, menyulut perpecahan di antara kita. Ketika godaan ini diamini, kita melupakan esensi agama yang sesungguhnya: mengantar manusia pada kemuliaan akhlak, bukan sekadar memperdebatkan simbol dan dalil lahiriah.
Inilah titik di mana kita diingatkan: agama bukan hanya soal identitas, melainkan perbuatan nyata. Agama adalah ketika kita menundukkan ego demi menolong mereka yang menderita. Agama adalah kepekaan untuk merasakan lapar orang lain dan kerinduan orang yang kesepian. Agama adalah cahaya yang bergerak di tangan kita setiap kali kita mengusap air mata seorang saudara. Dengan kata lain, agama adalah saat kita memilih melangkah di jalan kebaikan—meskipun pahit, menantang, atau tampak mustahil.
Setiap surah, kitab suci, maupun mantra suci pada akhirnya mengarahkan kita pada satu kesadaran: kita semua akan kembali kepada Pemilik Jiwa. Tubuh kita fana, harta pun sirna, yang lestari hanyalah ruh yang akan diminta pertanggungjawabannya. Di sinilah kedalaman makna agama sesungguhnya: memurnikan niat dalam setiap perbuatan, menjaga lisan agar tak melukai, dan merawat cinta yang dititipkan Tuhan dalam hati. Bila kita bersaing, maka bersainglah dalam kebaikan—biarkan ketulusan menjadi pakaian kita, dan kejujuran menjadi penuntun arah.
Bayangkan betapa indahnya dunia jika setiap orang memahami bahwa agamanya adalah perbuatan. Kebencian akan memudar ketika disinari ketulusan, dan sekat-sekat pemisah akan luluh oleh sikap saling menghormati. Kita mungkin tak pernah bisa “menyatukan” seluruh agama, tetapi kita mampu merayakan kebersamaan yang lahir dari nilai-nilai universal: cinta, kasih sayang, dan tanggung jawab atas titipan-Nya.
Akhirnya, seperti fajar dan senja yang setia berbagi cahaya pada semua insan, semoga kita pun belajar berbagi cahaya kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai pesan suci cinta kasih hanya berhenti sebagai slogan, sementara perilaku kita tak mencerminkan inti ajaran. Dengan menghidupkan nilai-nilai kemanusiaan, kita mewujudkan tujuan agung agama: mendekatkan manusia pada Tuhannya, serta mengikat satu sama lain dalam jalinan keharmonisan. Begitulah keimanan menemukan bentuk paling murninya—ketika menjadi perbuatan.